
 Coba
bayangkan keadaan Negara kita saat ini begitu rumit dan penuh dengan kesimpang
siuran dalam tatananan kepemerintahan, mulai dari system pemerintahan yang
notabenenya menganut system presidensial tapi peraktek yang ditimbulkan adalah
pemerintahan parlementer, salah satu cirinya adalah memiliki banyak partai,
sedangkan yang kita ketahui sendiri adalah system pemerintahan presidensial itu
hanya memiliki dua partai. Ketika praktek parlemeter ini secara tidak sadar
diberlakukan tentunya banyak hal yang dirugikan baik itu masyarakat dan Negara.
Coba
bayangkan keadaan Negara kita saat ini begitu rumit dan penuh dengan kesimpang
siuran dalam tatananan kepemerintahan, mulai dari system pemerintahan yang
notabenenya menganut system presidensial tapi peraktek yang ditimbulkan adalah
pemerintahan parlementer, salah satu cirinya adalah memiliki banyak partai,
sedangkan yang kita ketahui sendiri adalah system pemerintahan presidensial itu
hanya memiliki dua partai. Ketika praktek parlemeter ini secara tidak sadar
diberlakukan tentunya banyak hal yang dirugikan baik itu masyarakat dan Negara.
Bayangkan
saja setelah pemilu usai, politisi melakukan transaksi jual-beli suara, KPU
menyulap hasil suara. Caranya dengan memindahkan sejumlah suara kepada kandidat
tertentu, terutama dari partai atau calon legislatif peserta pemilu yang tak
memiliki saksi sejak tingkat TPS. Pemindahan atau penggelembungan suara partai
atau calon legislatif memiliki banderol harga. Suara pemilih seenaknya
diperjual-belikan. Calon dengan suara minim digelembungkan. Dalam iklim politik
yang demikian, kita sedang mencari dan memilih pemimpin formal. Maka,
pertanyaannya adalah: pemimpin formal macam apa yang bisa kita dapat dalam
iklim seperti itu? Jika pemimpin diperoleh dalam cuaca politik seperti di atas
maka harapan untuk membangun suatu kepemimpinan yang kuat dan bermartabat
semakin tipis bahkan lenyap.
Di
sisi lain, kita juga menemukan pemimpin informal yang muncul di berbagai kelas
sosial. Namun, banyak diantara kepemimpinan mereka yang terbentuk atas dasar
supremasi etnisitas, agama, dan golongan. Dukungan diperoleh karena
keberhasilannya membangun sentimen dan rasa benci pendukungnya terhadap
“yang-lain” dan “bukan mereka”. Kedua model pemimpin demikian sedang menguat
dan mengakar di Indonesia hari ini.
Pemimpin
lain yang muncul di tingkat lokal (terutama tingkat kabupaten) juga berangkat
dengan pola tak jauh berbeda. Umumnya adalah para pengusaha, birokrat ataupun
para jago (preman) yang memiliki banyak uang. Beberapa diantaranya disokong
pendamping dari kalangan artis untuk membantu pendulangan suara. Pada tingkat
ini, pemimpin-pemimpin yang muncul kebanyakan adalah figur yang menjadi tempat
bergantung hidup bagi tidak sedikit orang. Merujuk studi Onghokham, The
Thugs, the Curtain Thief, and the Sugar Lord (2003), mereka layaknya para sikep
di Jawa era kolonial Belanda, yakni pemilik tanah dan sawah. Warga desa non-sikep
menumpang (bergantung) hidup, dengan cara bekerja di sawah/tanah para sikep,
mendapat tempat tinggal di tanah sang sikep, namun tenaga kerjanya
menjadi milik para sikep. Para sikep memiliki kekuasaan yang
besar, karena kekuasaan monarki Mataram-Jawa tak lagi mampu menyentuh mereka
yang jauh dari pusat kerajaan, plus kekuasaan kolonial yang mampu mengerdilkan.
Kekuasaan para penguasa lokal hari ini pun nyaris serupa, tak bisa lagi
dikontrol semaunya oleh kekuasaan pusat atau nasional.
Politik
lokal hari ini memiliki kemiripan dengan pola hubungan sikep di era
kolonial. Banyak orang menjadi tokoh lokal karena menjadi tempat bergantung
hidup bagi banyak orang lainnya. Hubungan-hubungan inilah yang menopang jalinan
kekuasaan yang dibangun. Pertarungan politik lokal menjadi pertarungan antara
para “sikep”. Dalam situasi seperti ini kita dihadapkan pada persoalan
pencarian pemimpin dan bagaimana membangun kepemimpinan nasional. Para sikep
adalah pemimpin yang berhitung atas dasar untung-rugi dan akumulasi kekayaan.
Karakter ini yang juga menurun pada pemimpin lokal hari ini. Para sikep
era modern ini secara politik kekuasaannya jauh dari jangkauan kekuasaan pusat
(presiden), karena juga dipilih melalui mekanisme pemilihan umum yang
membuatnya punya legitimasi dukungan rakyat. Tak sedikit dari mereka yang
mengeluarkan aturan yang bertentangan dengan peraturan di atasnya, bahkan bertentangan
dengan konstitusi. Penguasa pusat tak kuasa lagi seenaknya menindak mereka
sebagaimana di era Orde Baru. Muncullah kekuasaan lokal yang menguat, dan
parahnya dipimpin para medioker.
Kalau
merujuk studi klasik Herbert Feith, The Decline of Constitutional Democracy
in Indonesia (1962), ada dua jenis kepemimpinan yang muncul di era
pergerakan nasional dan pasca revolusi, yakni “administrator” dan
“solidarity maker”. Para “administrators” meyakini bahwa kemampuan
untuk mencapai kekuasaan haruslah didasarkan pada keahlian teknis, dan juga
status melalui pencapaian atas penguasaan terhadap kemampuan teknis atau biasa
disebut mencapai kepakaran. Para administrators menilai bahwa posisi
kepemimpinan haruslah berada di tangan orang-orang seperti mereka, baik di
dalam birokrasi sipil, militer, dan partai-partai politik. Menjabat atas dasar
kemampuan pemikiran atau ide, sebagaimana pernah dikembangkan oleh kolonialisme
sebagai bagian dari upaya rasionalisasi, yaitu kaum terdidiklah yang memiliki
hak untuk memerintah.
Ditambahkan
juga bahwa martabat sosial haruslah merujuk pada pertimbangan serupa, yakni
bagi mereka-mereka yang memiliki kualifikasi akademis, keahlian professional
dan juga pengetahuan atau pengalaman seseorang dengan budaya dan dunia
intelektual, yang kemudian melahirkan intelektual kepemimpinan dan berpegang
teguh pada pancasila berladaskan untuk kemaslahatan rakyatnya. R.R

 Artikel
Artikel 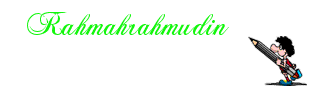
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
TERIMA KASIH ATAS KOMENTARNYA